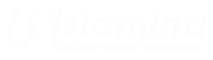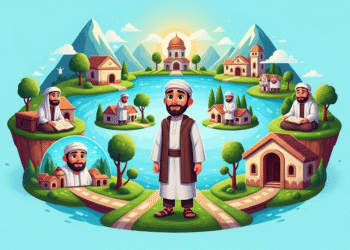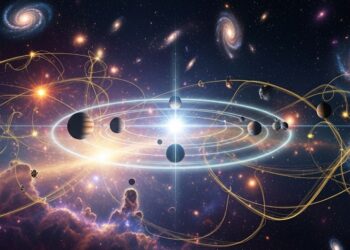Ketegangan antara subkultur sound horeg dan nilai dominan masyarakat tercermin dalam fatwa haram yang dikeluarkan oleh forum Bahtsul Masail Pesantren Besuk Pasuruan. Tidak hanya persoalan keterganguang masyarakat, fatwa ini menyandarkan salah satu konsiderannya bahwa sound horeg mengandung unsur maksiat (campur baur, berjoget vulgar). Aspek kepentingan sosiologis pun didasarkan pada kaidah dar’u al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-mashālih (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat). Inilah argumen utama dari pelarangan ini.
Mencari Solusi : Antara Represi dan Transformasi
Fenomena sound horeg adalah contoh nyata dari bagaimana budaya populer lokal berkembang di tengah keterbatasan. Ia bukan sekadar ekspresi kebisingan, tetapi cermin dari keresahan sosial, keterputusan generasi, dan pencarian ruang dalam tatanan yang tak ramah anak muda desa.
Maka, alih-alih hanya melarang, perlu ada upaya mediasi budaya: membuka ruang seni alternatif, menyediakan tempat hiburan yang terarah, dan mengedukasi anak muda tentang nilai estetika dan etika dalam berekspresi. Budaya tidak bisa hanya ditekan; ia harus diajak berdialog.
Fenomena sound horeg menandakan ada kesenjangan generasi dan kelas sosial yang harus dijembatani, bukan sekedar dihakimi. Kebutuhan ruang subkultur ini tidak untuk dimusnahkan secara total, tetapi bagaimana difasilitasi dengan membuat ruang yang lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu saja, catatan mudharat itu harus dihilangkan.
Pada akhirnya, saya ingin memetik nilai dakwah Wali Songo ketika berhadapan dengan budaya. Budaya dan tradisi itu tidak perlu dimatikan seberapa pun itu mempunyai dampak mudharat. Budaya itu memiliki akar yang kuat yang tidak mudah dimatikan. Cara terpenting adalah melakukan negosiasi nilai dengan menstranformasikan makna-makna baru dengan bentuk yang lebih sehat.
Sekali lagi, budaya tidak bisa dimatikan begitu saja, apalagi bila sudah menjadi bagian dari identitas dan ekspresi masyarakat akar rumput. Solusinya bukan represi, melainkan transformasi makna melalui pendekatan kultural dan spiritual yang membumi. Bagaimana praktek nyatanya?
Tentu ini bagian dari tugas tokoh agama dan organisasi keagamaan yang tidak sekedar mengandalkan represi hukum semata. Tokoh agama tidak bisa bekerja sendiri melalui mimbar dan menghukumi segalanya. Rekayasa budaya (cultural engineering) perlu dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini.
Adakah kemungkinan transformasi yang bisa dilakukan dalam melihat sound horeg ini? Adakah langkah pembinaan komunitas yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat dalam merubah arah ekspresi yang lebih sehat dan tidak mudharat? Adakah festival budaya yang transformatif yang bisa dilakukan pemerintah daerah dengan menggandeng pesantren untuk mewadahi fenomena ini?
Pilihan-pilihan kebijakan yang bijak itu masih banyak untuk dilakukan dari pada sekedar mengandalkan represi hukum. Dakwah it sejatinya proses negosiasi bukan konfrontasi. Bukan sekedar mengandalkan hitam-putih untuk melihat ragam masyarakat yang berwarna-warni. Kearifan dakwah dan hukum Islam sangat dibutuhkan dalam menyelasaikan persoalan ini.