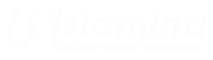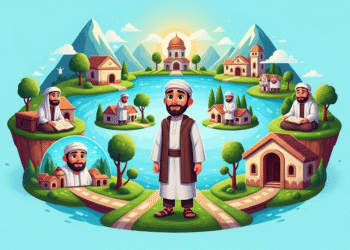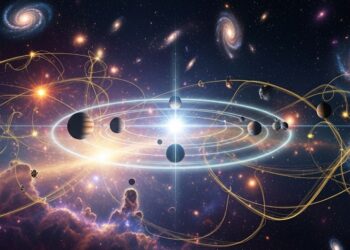Salah satu faktor penting yang mendorong interaksi damai adalah karakter dan sifat para pendakwah awal yang datang ke kepulauan ini bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pedagang dan guru sufi. Mereka adalah pedagang yang berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Interaksi ekonomi ini kemudian memfasilitasi kegiatan dakwah dan mengarahkan para ulama awal untuk lebih menekankan pada cara-cara persuasif.
Sejarah juga menggambarkan, bahwa karakter Islam yang disebarkan pendakwah awal tidak terlalu menekankan aspek hukum (fiqh). Sebagian sumber menyebutkan karakter sufi yang kuat, sehingga masalah moral, akhlak dan hakekat agama menjadi perhatian utama. Islam tasawuf, atau yang kita kenal dewasa ini dengan Islam yang bercorak sufistik, menekankan prinsip-prinsip pokok agama, seperti hubungan dengan Tuhan, menyempurnakan akhlak, dan keseimbangan hidup. Hal ini tidak berarti meninggalkan aspek syariat yang terkandung dalam fiqh Islam.
Karakter demikian membuat proses Islamisasi menjadi lentur, leluasa, tapi memiliki sumbangan positif di masa depan. Hal ini dapat dijumpai dari berbagai cerita rakyat tentang para wali. Para wali mempertahankan keindahan gaya bangunan tempat suci agama Hindu atau Budha dan memodifikasinya dengan membuat lapisan berjumlah lima sebagai simbol rukun Islam. Mereka juga tidak melarang pertunjukan wayang yang jelas-jelas hasil karya para pujangga Hindu. Para wali di Jawa mengubah alur cerita secara kreatif, dan memaknai kembali sejumlah simbol dan karakter yang ada dalam narasi utama.
Dalam aspek politik pun, para wali dan generasi ulama yang kemudian tidak memaksakan raja-raja menjadi subordinat dari kekhalifahan Islam yang saat itu sudah berjaya di Timur Tengah. Sebaliknya, mereka meneguhkan kekuasaan penguasa-penguasa lokal dengan mengangkat sebagai pemimpin agama di wilayah kekuasaan masing-masing.
Karakter Islamisasi Nusantara yang terbuka, yang bersedia menerima kebajikan dari kelompok lain, adalah capaian kepemimpinan tersendiri dari para ulama. Sikap ini tidak saja mampu menghindari kekerasan, tetapi juga membuka kesempatan untuk memahami Islam secara terbuka. Ketika berinteraksi dengan masyarakat lokal, para wali tidak saja terbuka menerima keragaman budaya, tetapi juga sadar bahwa hasil interaksi tersebut akan melahirkan pola pemahaman Islam yang kaya dan beragam.
Dalam perjalanannya, Islam di Indonesia memang tidak pernah berkembang secara seragam. Ada kelompok yang lebih dekat dengan tradisi sufi, ada yang lebih menekankan tradisi fiqh, dan ada pula yang bercirikan budaya rakyat dan adat istiadat. Munculnya keberagaman dalam menghayati Islam ini merupakan keniscayaan sosiologis dari proses interaksi kultural. Setiap kelompok dari berbagai strata sosial dan sub-kultur Islam memiliki keleluasaan mengekspresikan pemahaman Ke-Islamannya sendiri. Hasilnya, masing-masing kelompok dengan sendirinya terdorong untuk bersikap moderat dalam beragama.
*Disarikan dari pidato amanat Hari Santri Nasional 2021