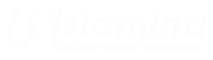Kesenian klasik asli Nusantara sudah hampir tidak digemari oleh mayoritas pemuda. Akibat arus globalisasi, perlahan budaya Nusantara akan lenyap. Wayang adalah salah satu kesenian yang sangat tua dan mungkin juga akan ikut punah.
Sekitar 1500 SM, ditemukan indikasi bahwa wayang telah ada. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat Jawa zaman prasejarah melakukan ritual penyembahan kepada arwah leluhur atau nenek -moyang atau kepada Hyang, Tuhan (Poespaningrat, 2005).
Memang, dahulu Nusantara Pra-Islam penduduknya masih menganut animisme dan dinamisme. Sunarto dalam Seni Gatra Wayang Kulit menuliskan jika munculnya wayang tidak dapat dilepaskan dari pemujaan roh leluhur yang disebut Hyang. Untuk menghormati dan memujanya, salah satunya dengan pertunjukan bayang-bayang. Sampai akhirnya pertunjukan bayang-bayang roh leluhur ini menjadi tradisi pada masyarakat agraris (Sunarto, 1997).
Teori asal-usul wayang pun juga berbeda. Ada yang berpendapat wayang budaya asli Nusantara, ada yang berpendapat wayang dari India. Seperti pendapat Holt, yang menulis bahwa sebelum Walisongo berdakwah dengan media wayang, para pendeta Hindu-Buddha sudah menggunakannya (Holt, 1967). Dan cara ini cukup efektif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha.
Masuk dalam periode Islamisasi. Kesenian wayang tak dapat dilepaskan dari peran salah satu Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. Ia merekonstruksi pewayangan dalam misi dakwah. Awalnya sempat dilarang karena masih ada nilai non-Islaminya, sampai akhirnya nilai-nilai syariah dan tasawuf dilebur dalam pertunjukan ini.
Wayang diantara Aturan Syariah dan Manuver Kalijaga
Perbedaan ijtihad para Imam Madzhab mengenai tidak diperbolehkannya menggambar atau melukis sosok manusia, sudah cukup memenuhi perdebatan di kalangan Muslim Sunni termasuk Walisongo.
Kalau dikaji lagi, terdapat beberapa hadits yang dijadikan patokan Ulama Sunni. Misalnya, dalam karya Imam Nawawi, kitab Riyāḍu aṣ-Ṣāliḥīn. Ada satu bab yang membahas tentang larangan menggambarkan hewan pada bagian luar barang, batu, baju, mata uang dirham, dinar, sarung bantal, dan sebagainya (an-Nawawi, 1992) .
Selain melarang penggambaran tersebut, juga ada larangan memasang di dinding, kain, baju, dan perintah merusak gambar-gambarnya. Walaupun judul bab ini menyebutkan semacam gambar hewan saja, dalam hadits-hadits-nya ada makna pelarangan yang cukup luas (Laki, 2021).
Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Iḥyāʾ ʿUlūm ad-Dīn, ada pendapatnya yang bisa kita garisbawahi. Ia berpendapat jika sesuatu hal yang tidak bagus ada dua jenis, yakni makruh dan haram. Lebih lanjutnya, andaikan melihat orang melakukan suatu kemakruhan, lebih baik menginformasikannya saja, jika perbuatannya itu makruh (al-Ghazali, 2005), bukan tindakan menghentikan.
Kembali ke Imam Nawawi. Dalam kitab lain, al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, ia mengutip hadits riwayat Muslim yang berisi ‘jika malaikat tidak akan memasuki rumah, bilamana di rumah tersebut ada anjing dan patung lalu sampai Rasulullah merobek kain yang bergambarkan kuda bersayap’. An-Nawawi kemudian menjelaskan: