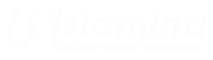Pengembangan yang dimaksud adalah peletakan sumber-sumber lain sebagai acuan-acuan yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam perumusan hukum dalam Islam, yaitu: ijmâ’ (konsensus), qiyâs (analogi), istishlâh (pencapaian maslahat), istihsân (kebaikan yang dicapai dengan rasio), istish-hâb (penetapan hukum yang telah berlaku sebelumnya), qawl shahâbîy (pendapat sahabat), syar’ man qablanâ (syariat agama pra-Islam), sadd al-dzarâ`i’ (tindakan preventif), ‘amal ahl al-madînah (tradisi penduduk Madinah), ‘urf (adat istiadat), al-istiqrâ` (observasi), al-akhdz bi aqall mâ qîla (pengambilan ukuran minimal yang dikemukakan) dan dalil al-‘aql (rasio).
Sumber-sumber hukum lain tersebut diberlakukan terkait dengan ajaran-ajaran qath’îy (kategoris) dan zhannîy (hipotesis) dalam Islam. Ajaran-ajaran qath’îy adalah ajaran-ajaran yang nilai-nilai universal dan fundamental, yang dalam al-Qur`an tercermin dalam ayat-ayat muhkamât.
Adapun ajaran-ajaran zhannîy adalah ajaran-ajaran yang bersifat jabaran (implementatif) dari ajaran-ajaran qath’îy tadi. Ajaran-ajaran zhannîy ini tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri. Karena itu ia terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi.
Dan yang harus diperhatikan, terutama dalam proses penerapan hudûd (ketetapan-ketetapan yang ditentukan Allah terkait hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu), keadilan, sebagai ajaran universal Islam, harus selalu menjadi pertimbangan utama.
Sekedar gambaran, hudûd adalah sekumpulan hukum yang secara eksplisit disebut dalam al-Qur`an. Hukum tersebut meliputi, umpamanya, hukuman bagi kasus zina dan pencurian. Penerapan hudûd ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tetutup, artinya tidak bisa berubah, hanya melihat tekstualitas al-Qur`an.
Sebagaimana dijelaskan oleh al-Syathibi dalam buku monomentalnya, “al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah”, bahwa al-Qur`an memiliki makna zhâhirîy dan bâthinîy. Sebagian besar umat Muslim hanya melihat makna zhâhirîy-nya saja, tanpa berusaha untuk menangkap makna bâthinîy-nya. Sehingga yang terjadi adalah penerapan hudûd secara keras, tidak ada kontekstualisasi. Artinya, tidak mau melihat konteks zaman dan tempat.
Dalam al-Qur`an, misalnya, disebutkan bahwa secara zhâhirîy, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Tetapi kalau dilihat makna bâthinîy-nya, tujuan Tuhan menurunkan ayat itu adalah membuat orang jera; tidak mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Di sinilah kontekstualisasi berlaku.
Pada zaman Jahiliyah, sebelum Islam, hukum potong tangan sudah ada, dan al-Qur`an pun dalam menentukan hudûd tidak serta-merta menghapus hukum-hukum yang berlaku di masyarakat kala itu; tidak melabrak arus. Hukum potong tangan ketika itu masih relevan, mengingat watak orang Arab kala itu sangat keras, ganas dan primitif. Sehingga, mau tidak mau, al-Qur`an ikut membenarkannya.
Di negara-negara lain, hukum yang berlaku tentu saja berbeda dengan masyarakat Arab. Di Indonesia misalnya, hukuman bagi pencuri yang paling banyak diterapkan adalah kurungan penjara, atau hukuman lain yang lebih ringan. Di sini yang berlaku bukan lagi makna zhâhirîy—ayat yang menegaskan potong tangan—, tetapi makna bâthinîy-nya berupa tujuan untuk membuat orang jera dan tidak mengulangi kesalahannya.
Selama tujuan itu tercapai, hukuman apapun bisa dibenarkan, asalkan tentu saja tidak memperkosa hak-hak dasar. Ketika misalnya, seorang pencuri bisa jera dengan nasehat, maka hukuman seperti potong tangan atau penjara bisa saja tidak perlu diberlakukan.
Di dalam bukunya, “Selamatkan Islam dari Muslim Puritan”, Khaled Abou el-Fadhl mengatakan bahwa penerapan hudûd sebenarnya tidak perlu terlalu keras. Menurutnya, dalam beberapa kasus, al-Qur`an memberikan isyarat-isyarat yang menekankan hal itu. Misalnya, ketika menyebutkan syarat-syarat dalam penerapan hudûd. Meskipun hudûd mencakup hukuman pidana yang keras, namun aspek kekerasan dalam hudûd ini menjadi terkurangi oleh kenyataan bahwa syarat pembuktian yang dibutuhkan untuk bisa memberlakukan hukuman sangat detail dan banyak sekali persyaratannya.
Dan tentu saja hal tersebut sangat menyulitkan penerapan hukuman dan karena itu jarang terimplementasikan. Misalnya, untuk membuktikan kasus perzinahan, yang dihukum dengan seratus cambukan, empat saksi mata harus bisa membuktikan bahwa—maaf saja—mereka melihat penis si pelaku sepenuhnya dimasukkan ke dalam vagina.
Itu jelas merupakan standar pembuktian yang teramat sulit. Dan yang lebih sulit bila beberapa dari empat saksi itu bersaksi bahwa mereka melihat peristiwa itu, sementara satu atau lebih dari empat saksi itu bersaksi bahwa mereka tidak melihat peristiwa itu, maka mereka yang mengklaim telah melihat peristiwa itu secara penuh (kelompok yang pertama) dihukum atas tuduhan memfitnah.
Jadi, jika ada orang yang datang membawa pernyataan tanpa bukti yang tidak dibenarkan oleh yang lain, ia melakukan ini semua dengan penuh resiko. Tentunya, hal ini berfungsi, selain untuk menghindar dari penuduhan yang tak dibenarkan mengenai perilaku seks yang tidak sah.[]