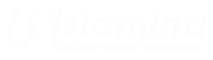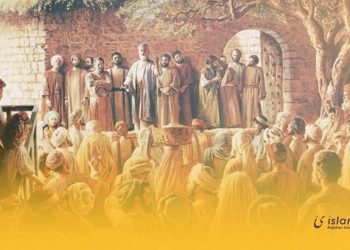Bersama dengan pesatnya perkembangan Muslim di Tiongkok, Mongol menciptakan kebijakan penting bagi kelangsungan Muslim di Tiongkok, yaitu mengasimilasikan Muslim dalam budaya Tiongkok. Mirip-mirip dengan kebijakan Orde Baru yang mewajibkan asimilasi para imigran Tiongkok di Indonesia, kebijakan Mongol meniscayakan komunitas Muslim untuk keluar dari zona “isolasi” dan mulai melebur dengan realitas budaya sosial politik pribumi.
Hingga periode kekuasaan Dinasti Ming (1368-1644 M), Muslim Tiongkok benar-benar terasimiliasi dalam budaya lokal. Mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing, tetapi warga negara Tiongkok yang memilik identitas sendiri. Mereka mengadopsi adat, bahkan nama Tionghoa, dengan tetap meneruskan tradisi mengabdi pada pemerintahan kerajaan sebagai pejabat public dan pemimpin militer.
Hingga periode kekuasaan Dinasti Ming (1368-1644 M), Muslim Tiongkok benar-benar terasimiliasi dalam budaya lokal. Mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing, tetapi warga negara Tiongkok yang memilik identitas sendiri.
Gerak asimilasi yang berlangsung lintas generasi ini kemudian melahirkan salah satu tokoh Muslim terkemuka hingga saat ini bernama Zheng-He, populer sebagai Laksamana Cheng Ho (1371-1433 M), seorang penjelajah besar dunia. Ia adalah seorang Hui (Muslim Tiongkok) dari wilayah Yunnan selatan. Cheng Ho dekat dan menjadi sosok kesayangan Dinasti Ming dan ditugasi memimpin armada kapal harta karun.
Sang Laksamana memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut ketiga kapal Colombus. Ia bertanggungjawab untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjelang hubungan diplomatik dengan tempat tersebut. Pelayaran Cheng Ho mencapai puluhan negara di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Cheng Ho mendapat puncak popularitasnya di Asia Tenggara. Ia dianggap sebagai tokoh yang membantu penyebaran Islam di kepulauan Melayu. Buktinya, masjid-masjid di wilayah itu diberi nama Cheng Ho. Ada juga masjid yang menisbatkan namanya pada tokoh serupa di Palembang, Masjid Cheng Ho Sriwijaya.
Cheng Ho menjadi sosok yang mampu menjadikan dirinya terhormat, baik di kalangan Muslim maupun masyarakat Tionghoa. Cheng Ho merupakan representasi Muslim di Tiongkok. Ia seorang Tionghoa asli, tetapi juga seorang Muslim yang taat. Sosok Cheng Ho menjadi bukti bahwa tidak ada kontradiksi di antara kedua identitas tersebut, Islam dan Tionghoa.
Karena itu bisa dikatakan bahwa “setting default” relasi Islam dan Cina adalah relasi mutualisme yang harmonis. Hubungan ini tidak berlaku dalam ranah lokal di Tiongkok saja, namun juga terbawa hingga konteks nasional di Nusantara melalui warisan-warisan budaya akulturasi Islam-Tiongkok. Jika kemudian muncul sentimen anti-Cina atau anti-Tiongkok, maka itu sebetulnya tidak merepresentasikan sikap Muslim yang toleran, melainkan murni sentimen politis yang rentan mengganggu hubungan baik yang sudah lama terjalin.