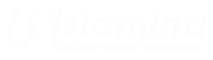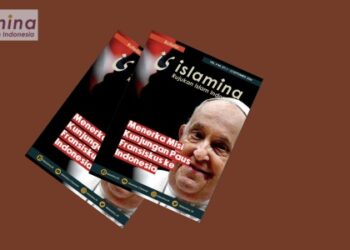Melalui Kongres Berkebaya Nasional (KBN) yang digelar secara virtual oleh Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) pada 5-6 April 2021, dimantapkan langkah untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan tak benda ke UNESCO sekaligus mengupayakan kelahiran Hari Berkebaya Nasional (Kompas, 25 April 2021). PBI memilih kebaya kutubaru atau kebaya kartini karena sangat khas Indonesia.
Bukan asal memilih waktu KBN mengupayakan dua hal penting ini. Di bulan April, Indonesia menghormati Kartini. Para perempuan terutama, semakin memuja dan memaknai kebaya. Kebaya panjang Kartini adalah cikal bakal kebaya Indonesia yang kini jadi busana nasional. Kebaya bukan soal jenis busana. Kebaya adalah baju identitas, baju pemikiran yang membalut juang di pergerakan kebangsaan yang cenderung maskulin. Dalam surat-surat, Kartini kentara menggugat tentang tubuh perempuan. Kebebasan tubuh adalah permulaan kebebasan pikir meski tidak diiringi kebebasan berbusana. Kartini menyadari, kebaya yang kini tengah dirayakan sebagai kekayaan nasional, bukanlah busana yang fleksibel nan membebaskan.
Kartini pernah mengeluh dengan gemas lewat surat yang ditujukan pada E.H. Zehandelaar (18 Agustus 1899), “Kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus melakukannya dengan perlahan-lahan. Dengan langkah pendek-pendek dan sopan, aduh perlahan-lahan sekali seperti siput. Kalau ia berjalan lebih cepat, maka ia dicaci maki diibaratkan kuda berlari” (Sulastin Sutrisno, 2014). Kita membayangkan Kartini mengenakan kebaya, bahkan jadi pakem jika kita mendapati kebanyakan foto Kartini.
Namun, Kartini tak mau terpakem para sistem yang menjadikan perempuan tidak boleh bersekolah, membaca, menulis, atau belajar bahasa. Kebaya memang dilekatkan pada tubuh perempuan untuk menjaga kesantunan dan mengontrol gerak tubuh, tapi emansipasi adalah keniscayaan tanpa harus melepas identitas kejawaan yang turut ditentukan oleh busana. Kartini tetap modern secara intelektualitas meski tidak berbaju rok atau terusan ala Eropa.
Nafas kejawaan dan keinginan bebas dalam kebaya juga dinarasikan oleh Hanna Rambe dalam novel Mirah dari Banda (2010). Mirah bukan seorang terpelajar, ‘hanya’ seorang buruh perek (perkebunan) pala di Bandaneira. Mirah cerminan perempuan Jawa yang paling tabah menerima nasib. Namun, ketabahan Mirah justru berarti perlawanan saat kebaya harus diganti oleh busana ala Barat karena status sebagai nyai atau gundik tuan Belanda.
Mirah merasakan segan. Ada pernyataan yang begitu dramatis, sendu, nelangsa sekaligus legowo, “hanya kain dan kebayalah pakaian yang saya kenal sepanjang hidup saya. Dengan pakaian ini saya meninggalkan masa kanak-kanak, melewatinya bersama semua orang bernasib malang di perek Ulupitu. bagaimana saya harus melepaskannya? Saya tak pernah memakai rok, dan takut sekali ditertawakan atau dituduh meniru-niru perempuan Belanda di Neira.” Kebaya menafsirkan diri agar tidak hilang dalam lintasan sejarah yang sering buram dan tidak adil.. Mirah tidak butuh pernyataan sok idealis buat bertahan dalam kebaya sebagai kesejatian.