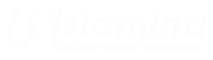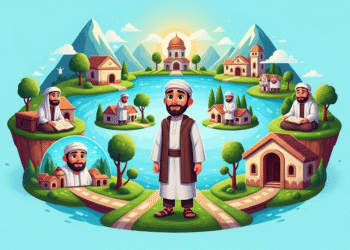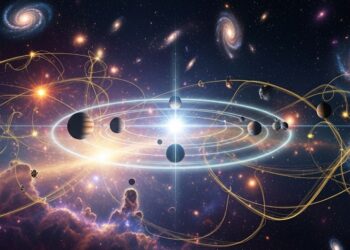Perdebatan tersebut sudah ada semenjak Abu Hamid Al-Ghazali (w. 1111 M). Secara bahasa, kata “sains” berasal dari bahasa Latin yang berarti “mengetahui”, akhirnya sains tidak sekadar berarti pengetahuan, terutama pengetahuan tentang dunia alamiah. Yang paling penting, pengetahuan ini diatur dengan cara sistematis dan rasional.
Sains bahasa Inggrisnya adalah science yang berarti suatu cabang dari ilmu pengetahuan atau pelajaran yang berhadapan dengan suatu benda dari fakta atau kenyataan secara sistematis, menyusun dan pementasan eksploitasi dari hukum yang umum “ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pasti.”
Umumnya sains dianggap merupakan usaha untuk mencari keteratuan dalam pengamatan manusia pada alam sekitarnya. Banyak orang yang berfikir bahwa sains adalah proses mekanis dalam mengumpulkan fakta-fakta dan membuat teori. Hal ini tidak benar. Sains adalah suatu aktifitas kreatif yang dalam banyak hal menyerupai aktivitas kreatif pikiran manusia.
Namun, pengamatan memerlukan imajinasi, karena ilmuwan tidak akan pernah bisa memasukan semuanya dalam satu deskripsi mengenai apa yang mereka amati. Dengan demikian, ilmuwan harus melakukan penilaian mengenai apa yang relevan dengan pengamatan mereka. Sebagai contoh, ditemukannya pertemuan dua lautan yang satu tawar sedang yang lainnya asin, hal ini disebabkan perberbedaan kadar dari salinitas dari masing-masing samudra (Douglas, 2001).
Teori-teori besar sains bisa dibandingkan, sebagai hasil karya kreatif, dengan karya-karya besar pada bidang seni dan sastra. Teori yang dihasilkan dari inspirasi pikiran manusia, tidaklah semuanya sebuah teori dapat dibuktikan dengan pengujian, disebabkan tidak adanya alat pengukuran yang sempurna.
Proses penggantian satu teori dengan yang lain, merupakan suatu subyek penting dalam filosofi sains. Ketika muncul ketidak sesuaian antara teori dan percobaan, teori baru harus dirumuskan untuk menghilangkan ketidak sesuaian tersebut. Seringkali teori dianggap memuaskan hanya dalam kondisikondisi terbatas; teori yang lebih umum mungkin memuaskan tanpa adanya batasan-batasan tersebut (W. Jewett, 2001).
Namun, seperti yang pernah ditulis oleh Abul Mustaqim, bahwa seiring dengan perkembangan demikian, ada sebagian ulama yang menilai kecenderungan tersebut merupakan bentuk apologis (takhalluf bi al-difa’) yang tidak perlu dilakukan. Karena teori ilmu pengetahuan tidak perlu dicari-cari lagi dalilnya dari al-Qur’an, sebab ia murni ilmiah dan obyektif. Sedangkan legitimasi ayat al-Qur’an subyektif, tergantung keimanannya terhadap kebenaran ayat al-Qur’an. Sehingga tidak mencocok-cocokan atau memaksakan (takalluf) kebenaran ilmiah dengan ayat al-Qur’an yang belum tentu dipahami pengertiannya pada saat pewahyuan (Mustaqim, 2006).