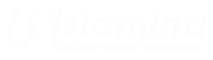Dari itu, kredibilitas intelektual merupakan syarat paling menentukan. Dan orang yang mempelajari filsafat, di samping harus mengambil pemikiran filsafat yang dianggap benar tanpa melakukan distorsi, juga harus menempatkannya pada posisi yang semestinya. Menggunakan filsafat bukan pada tempatnya, seperti membohongi orang lain, berbangga diri dengan apa yang dimilikinya, atau dengan tujuan menopang aliran dan politik tertentu, menurut Ibnu Rushd adalah perbuatan tercela.
Dapat dilihat, Ibnu Rusyd sebenarnya ingin membuktikan bahwa para penentang filsafat tidak mempunyai persyaratan tersebut. Mereka yang mampu memahami filsafat dengan benar serta menempatkannya pada posisi yang semestinya tidak akan mengharamkan filsafat. Al-Ghazali, yang dalam hal ini dipandang telah mengkafirkan filsafat, adalah figur yang dianggap tidak memenuhi persyaratan itu.
Sebetulnya, dalam hal serangan terhadap filsafat, al-Ghazali bukanlah orang pertama. Sebelumnya, tokoh-tokoh ahli kalam seperti al-Asy’ari dan al-Baqillani telah memulainya dengan memerangi gerakan atheisme dan filsafat secara bersamaan. Bahkan tidak hanya para ahli kalam, seorang sufi seperti Haris al-Muhasibi juga melakukannya. Dalam memerangi filsafat, ia memerankan dirinya sebagai seorang ahli kalam sekaligus sufi. Model semacam inilah yang nampaknya dikembangkan oleh al-Ghazali.
Perlawanan terhadap filsafat ternyata juga terjadi dalam pemikiran Kristen dan Yahudi. Yahya al-Nahwi adalah akademisi Kristen yang telah melakukan perlawanan terhadap filsafat jauh sebelum kelahiran al-Ghazali. Pemikiranya sedikit banyak berhasil mempengaruhi paradigma berpikir al-Ghazâlî dalam memerangi filsafat.
Meski demikian, serangan al-Ghazali tidak bisa disamakan dengan sebelumnya. Sampai saat ini belum ditemukan satupun akademisi yang mampu menyamai atau bahkan melebihinya. Salah satu karyanya, “Tahâfut al-Falâsifah”, dinobatkan sebagai karya terbesar yang nyaris tidak terbantahkan. Dalam artian, belum ada yang mampu mengikis pengaruhnya dalam peradaban Islam. “Tahâfut al-Falâsifah” merupakan sebuah kitab yang dipandang berisikan “fatwa pengharaman” seorang agamawan terhadap filsafat.
Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa faktor pengkafiran al-Ghazali terhadap filsafat tidak kembali pada esensi filsafat itu sendiri. Pengkafiran tersebut lebih terkait dengan tujuan ideologi tertentu, yaitu ideologi negara Saljuk yang berada di bawah naungan aliran Asy’ariyah; ini jika dilihat dari kritik al-Ghazali yang hanya ditumpahkan kepada pemikiran Ibnu Sina, padahal banyak filsuf lain yang mempunyai pemikiran lebih berbahaya dari Ibnu Sina, sebut saja misalnya Ibnu Ruwandi, yang luput dari serangan al-Ghazali.
Pengkafiran tersebut lebih diakibatkan oleh adanya bahaya ideologis filsafat Ibnu Sina yang pada waktu itu dianggap akan merobohkan aliran Asy’ariyah. Pemikiran Ibnu Sina yang diusung oleh aliran Syi’ah Ismailiyah atau Imamiyah dianggap sebagai “badai” yang akan menggoyahkan ideologi Abbasiyah, tempat al-Ghazali bernaung. Maka, pengkafiran terhadap filsafat secara menyeluruh tidak bisa dibenarkan dalam etika intelektual.
Pengkafiran terhadap filsafat, dengan mengacu pada teks-teks Ibnu Sina, menuntut Ibnu Rusyd melakukan purifikasi terhadap filsafat dari distorsi penerjemahan yang tidak akurat. Upaya tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pegangan al-Ghazali dalam mengkafirkan filsafat bukanlah representasi dari pemikiran filsafat itu sendiri, melainkan hanya filsafat Ibnu Sina atau Aristoteles yang telah mengalami distorsi. Purifikasi tersebut juga dimaksudkan untuk membuktikan adanya kebenaran yang sama antara agama dan filsafat.
Purifikasi yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah purifikasi filsafat Aristoteles yang dianggap sebagai representasi kematangan pemikiran Yunani. Aristoteles dianggap mampu meluruskan dan mengembangkan filsafat para pendahulunya. Filsafatnya merupakan penjelmaan dari komplikasi filsafat terdahulu. Keluar dari filsafat Aristoteles, dengan menjadikan filsafat pendahulunya sebagai acuan, tidak akan mampu mendesain filsafat lebih bagus dari pada filsafat Aristoteles, seperti aliran Neo-Platonisme yang ditengarai jauh dari nilai ilmiyah dengan menjadikan Plato sebagai acuan dalam berfilsafat.
Dalam mempurifikasi filsafat Aristoteles, Ibnu Rusyd melakukan peringkasan, komentar, harmonisasi dan sekaligus melakukan penafsiran. Itu semua dilakukannya demi membersihkan filsafat Aristoteles dari pelbagai distorsi. Ibnu Rusyd berusaha membersihkan filsafat Aristoteles dari kerancuan yang ditimbulkan oleh pemikiran lain yang tidak termasuk dalam bingkai filsafat Aristoteles. Kemampuannya mengomentari filsafat Aristoteles telah menghantarkan dirinya meraih gelar sebagai komentator terbaik terhadap filsafat Aristoteles, bahkan pemikirannya menjadi pintu gerbang proses pencerahan di Eropa.[]